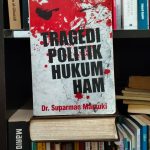Reformasi ditandai dilengserkannya Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998. Mahasiswa menuntut agenda reformasi (Tirto) berupa adili Soeharto dan kroni-kroninya Soeharto, laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan dwi fungsi ABRI, laksanakan Otonomi Daerah seluas-luasnya, tegakkan supermasi hukum dan ciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selama 27 tahun reformasi, salah satu yang masih menjadi pekerjaan terbesar dan kompleks dari sisi politik adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Sipil dan Politik (HSP) dan Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (HESB).
Dalam buku Tragedi Politik Hukum HAM (Maret 2011) karya Suparman Marzuki yang mengkaji politik hukum dalam menyiapkan perangkat perundang-undangan HAM sebagai dasar hukum bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu guna menjelaskan pandangan bahwa kegagalan penegakan hukum HAM dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu memang disiapkan untuk gagal.
Dalam kajian itu, Suparman Marzuki menampilkan politik hukum HAM sejak era orde lama, orde baru, reformasi, hingga masa kini (2011) dengan dinamikanya, juga membahas negara hukum, demokrasi demokrasi, konfigurasi politik dan produk-produk hukum HAM sepeninggal Soeharto guna melihat kerangka makro hukum dan politik pembuatan peraturan perundang-undangan HAM yang menjadi dasar hukum penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.
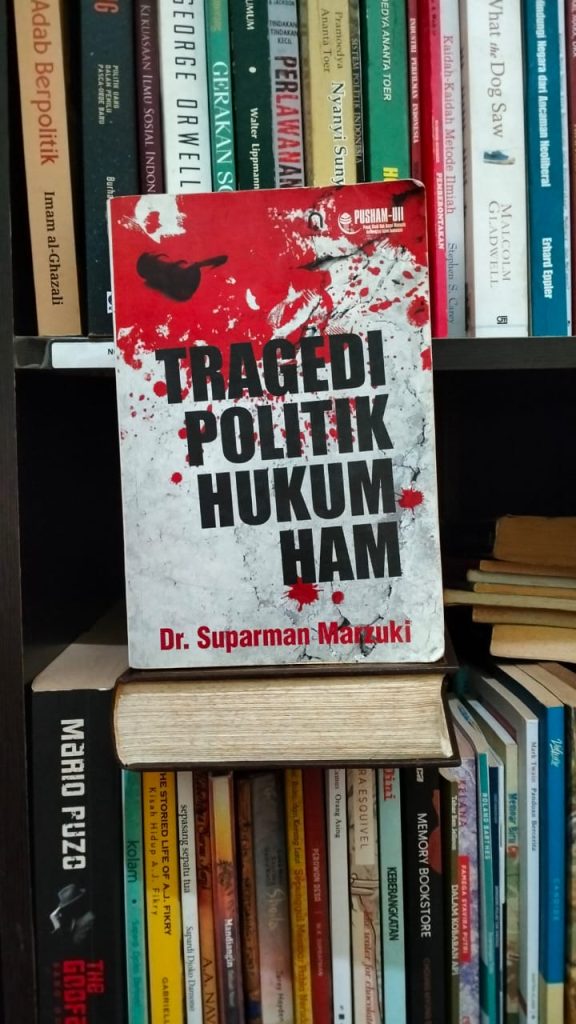
Salah satu kritikan Suparman Marzuki dalam BAB Politik Hukum dan HAM di era Demokratis menerangkan, konstitusi Indonesia saat ini memuat ketentuan yang melindungi serangkaian HAM yang mencakup HSP dan HESB. Jaminan konstitusi terhadap HAM tentu saja tidak boleh berhenti sampai di ditingkat norma dasar, tapi harus diturunkan menjadi kebijakan (politik) hukum yang lebih operasional, termasuk prosedur dan birokrasi untuk mempertahankan dan memperjuangkannya bila terjadi pelanggaran HAM sehingga pelanggaran HAM tidak berulang.
Lebih lanjut, Marzuki setuju dengan konsepsi hukum HAM responsif yang bersumber dari Phillippe Nonet dan Philp Selznick, yaitu pembuatan hukum harus diproses secara partisipatif dengan substansi yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial sesuai realitas HAM di Indonesia. Bagian pentingnya adalah sifat afirmatif yang dilegalisasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai respon atas kebutuhan riil masyarakat. Jika pada aspek HSP prinsip kebebasan dikerangka sebagai ruang pemenuhan hak-hak, bidang HESB dikonstruksikan sebagai aksi afirmatif untuk tujuan equal opportunity agar kelompok atau golongan tertentu yang rentan memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain yang kuat. Sebagai tindakan afirmatif, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang memberi posisi hukum HESB sebagai hak yang bisa dikomplain pemenuhannya secara hukum (justiciable).
Analisis Marzuki bahwa HSP dan HESB adalah problem utama dan kebutuhan dasar mayoritas rakyat Indonesia karena belum pernah menikmati perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM sepanjang sejarah Indonesia. Memperioritaskan produk hukum HAM yang menjamin HSP dan menomorduakan HESB sama artinya tidak memberikan jaminan kepada HSP kepada mayoritas rakyat. Sebaliknya, memperioritaskan HESB dan mengabaikan HSP sama dengan apa yang dilakukan negara-negara otoritarian terhadap penduduknya yang menjaga “perut rakyatnya tetap kenyang”, tapi membelenggu akal sehat.
Fredom from fear (HSP) dan freedom from want (HESB), dua sisi mata uang yang sama. Dalam pembukaan HESB juga ditegaskan kondisi ideal manusia ditandai oleh terwujudnya freedom from fear dan freedom from want hanya dapat dicapai bila setiap orang dapat menikmati HSP dan HESB. Kenyataannya HESB cenderung dipandang sebagai tujuan yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya dalam kondisi apapun. Semngat reformasi menyusul jatuhny Soeharto telah membuka peluang bagi perubahan kondisi HAM di Indonesia, HSP maupun HESB.
Prioritas pada HSP lazim dilakukan oleh pemerintahan pengganti, selain sebagai koreksi terhadap konsep dan praktik sistem kekuasaan otoritarian yang memang mengabaikan HSP, sekaligus sebagai pondasi bagi bangunan sistem politik demokratis yang akan dibangun. Berbeda dengan HESB, tak sedikit rezim otoritarian yang justru memenuhi HESB dengan baik sekaligus merampas HSP, karena terma ekonomi dan pembangunan digunakan sebagai alat legitimasi rezim. Singapura, China dan negara di Timur Tengah contoh negara tidak demokratis, tapi sangat memperhatikan HESB, terutama hak sosial dan ekonomi.
Berbeda dengan Indonesia, sejak merdeka bahkan sejak penjajahan, rakyat Indonesia tidak menikmati kedua hak tersebut sekaligus. Di era penjajahan, orde lama dan orde baru HSP diberangus sementara HESB tidak diberikan. Kedua hak itu hanya dinikmati oleh segelintir elit penguasa atau segelintir orang kaya. Mayoritas rakyat Indonesia hingga kini belum menggenggam kemerdekaan sipil, politik, sosial dan ekonomi.
Marzuki menilai urgensi pemenuhan dan perlindungan HESB, pertama, HESB mencakup ragam masalah paling utama dialami manusia sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan dan perumahan diantara kebutuhan pokok bagi manusia. Realitasnya banyak manusia di dunia tidak punya akses terhadap kebutuhan pokok mereka, jangankan mempngaruhi kebijakan penguasa tentang survival mereka sehari-hari. Kedua, HESB tidak bisa dipisahkan dengan HAM lainnya. Interdependensi HAM adalah realita yang tidak bisa dihindari saat ini. Hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat, misalnya, tidak akan berarti bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup membiayai sekolah. Ketiga, HESB mengubah kebutuhan menjadi hak. Atas dasar keadilan dan martabat manusia, HESB memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai hak yang harus diklaim (right to claim) dan bukannya sumbangan yang didapat (charity to recieve).
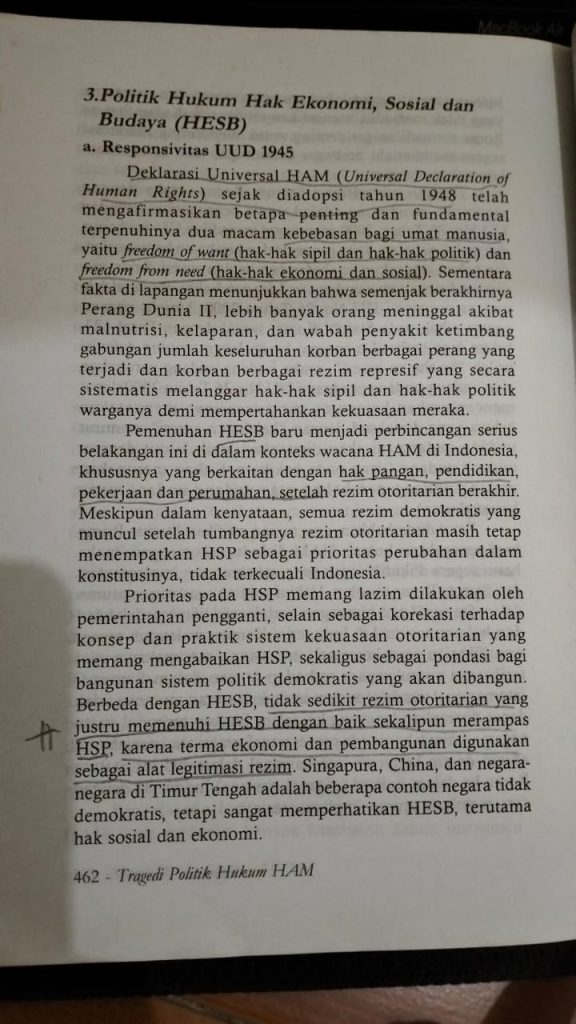
Menurut Marzuki, tantangan Indonesia di era desentralisasi adalah potensi terjadinya pelanggaran HESB yang besar, baik karena kesengajaan (crime by comission), karena pembiaran (crime by omission) maupun karena dimediasi (mediated crime).
Tindakan sengaja bisa terjadi bila pemerintah atau pemerintah daerah secara sengaja membiarkan rakyatnya tidak memperoleh hak-hak dasarnya untuk hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga tetap miskin, terbelakang, tidak sehat dan tidak berpendidikan.
Tindakan pembiaran terjadi bila pemerintah tidak mengambil tindakan atau diam atas suatu keadaan padahal bisa melakukan tindakan itu, pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM karena pembiaran. Penduduk yang menderita kelaparan, gizi buruk atau tidak berpendidikan dan pemerintah diam atas itu; lebih-lebih apabila negara atau daerah bersangkutan memiliki kekuatan ekonomi untuk melakukannya, pemerintah telah melakukan kejahatan atau kekerasan karena pembiaran.
Kejahatan karena dimediasi adalah hasil dari intervensi pemerintah secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain. Pengaruhnya memang tidak langsung dirasakan, tapi dalam waktu tertentu dampak itu dirasakan; eksploitasi alam, penebangan hutan misalnya adalah jenis tindakan mediated crime, yang dalam rentang waktu tertentu mendatangkan bencana banjir, longsor, dan lainnya.
Salah satu usulan Marzuki adalah merevisi UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan pengaturan berupa memasukkan kewajiban kepada korporasi untuk ikut bertanggungjawab memenuhi dan melindungi HESB. Sekalipun sudah diatur dalam UU lain, tapi pengaturan tentang ini di UU HAM sangat diperlukan karena UU ini adalah UU khusus tentang HAM sehingga memiliki bobot normatif lebih kuat.
Substansi pengaturan bidang ini sangat urgen karena korporasi sesungguhnya memiliki kekuatan modal untuk ikut bertanggungjawab melakukan pemenuhan HAM dan perlindungan HAM. Pemenuhan HAM menyediakan lapangan kerja dengan gaji yang layak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan. Demikian pula memiliki kemampuan melindungi dengan menjamin terpenuhinya hak-hak pekerjanya, termasuk tidak diberhentikan, atau kalaupun diberhentikan ada jaminan pesangon yang manusiawi. Selain itu, dana Corporate Social Respinsibility (CSR) yang dimiliki korporasi sudah seharusnya diberikan dengan paradigma pemenuhan dan perlindungan HAM sebagai hak kelompok marjinal dan tanggungjawab kemanusiaan, dan bukan hadiah, derma atau charity.
Disertasi Suparman Marzuki (2005-2010) yang kemudian menjadi buku pada Maret 2011, menemukan wujudnya tatkala di tahun yang sama saat buku terbit, PBB menerbitkan Panduan Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, yang intinya dunia usaha dalam rantai bisnisnya salah satunya di dalam maupun di luar operasional perusahaan menghormati HAM, ada konsekuensi hukum bila tak dijalankan.
Namun, panduan prinsip Bisnis dan HAM di Indonesia masih sebatas wacana diterapkan secara sukarela bukan kewajiban. Dari Era SBY hingga Jokowi, terbit kebijakan berupa strategi nasional bisnis dan HAM, namun hanya sebatas dokumen sukarela, bukan wajib diikuti oleh perusahaan.
Tentu, dampak kebijakan pemerintah tak pula bisa menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi di sektor sumberdaya alam. Yang terjadi kian masifnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi: bukan saja menghancurkan hutan, flora, fauna, tanah, sungai, laut, kerusakan lingkungan hidup, tapi menghancurkan kehidupan makhluk hidup.
Bila pemerintah dan dunia usaha tak punya inisiatif aktif menyelesaikan persoalan HAM, tuntutan masyarakat akan terus menghantui mereka sehingga pelanggaran HAM di sektor SDA-LH berdampak pada hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan bahkan pertahanan keamanan.
Peristiwa Minggu Keempat Agustus-Awal September 2025 gara-gara pernyataan dan joget-joget legislator, penjarahan rumah artis dan Menteri, korban nyawa hingga demonstran menghilang hingga terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM oleh polisi dan pemerintahan Prabowo Subianto, berakar pada kondisi HESB masyarakat Indonesia yang tidak dipenuhi oleh pemerintah karena membiarkan korupsi merajalela salah satunya memberikan izin dan konsesi sumber daya alam Indonesia kepada taipan dan segelintir pengusaha hitam yang selama ini membiayai para politisi dalam pemilihan umum yang berdampak pada kemiskinan masyarakat adat dan tempatan dan masyarakat yang bergantung pada kehidupan makhluk hidup lainnya.
Menyelesaikan HAM sektor SDA-LH memberi keadilan bagi mereka yang berjuang hingga merenggut nyawa, sembari kita bersatu melawan pelanggaran HAM berat lainnya. Mereka yang terpilih dari proses demokrasi berhutang pada mereka yang berjuang saat reformasi, yaitu melanjutkan cita-cita reformasi yang dibajak kroni orde baru, pengusaha hitam dan oligarki.
Jangan-jangan, cara-cara penjarahan di rumah Sahroni, Uya Kuya, Eko Patria hingga Sri Mulyani akan sampai ke rumah-rumah para politisi dan segelintir orang kaya yang berbisnis dengan cara-cara ilegal?
***